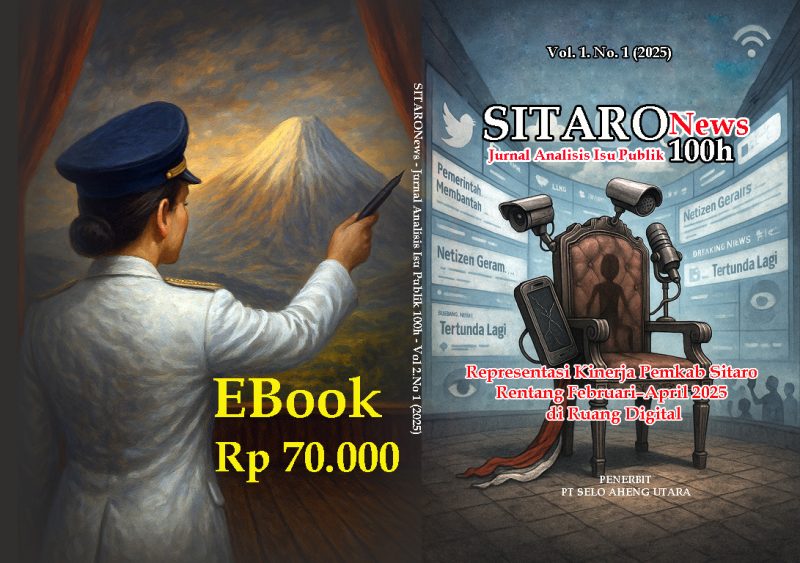Di tengah gencarnya publikasi keberhasilan pemerintah di berbagai kanal media daring, kita dihadapkan pada kenyataan yang justru berlawanan di ruang media sosial. Di satu sisi, media memberitakan pelayanan publik yang membaik dan tata kelola yang progresif; di sisi lain, masyarakat di media sosial mengeluhkan hal yang sama dengan nada frustrasi. Ini bukan hanya perbedaan persepsi—ini adalah gejala diskrepansi narasi dan realitas.
Dalam riset konten yang saya lakukan terhadap kanal media online dan media sosial, ditemukan bahwa isu pelayanan publik dan transparansi menjadi titik krusial dari kesenjangan tersebut. Media cenderung menyajikan narasi positif, sementara publik di media sosial menunjukkan kecenderungan kritis—bahkan sangat kritis.
Media dan Framing: Kenyataan yang Dibingkai Rapi
Media online masih menjadi sumber utama informasi publik, tetapi framing yang digunakan menunjukkan kecenderungan menghaluskan kenyataan. Isu pelayanan publik, misalnya, mendominasi pemberitaan (29,04%) dengan nilai framing tinggi. Artinya, konten-konten ini menekankan capaian pemerintah, pencitraan layanan, atau sekadar reproduksi dari rilis resmi tanpa kritik yang mendalam.
Begitu pula dengan kebijakan sosial yang juga mendapat sorotan positif. Namun yang mengejutkan adalah isu transparansi dan tata kelola, yang hanya menempati 16,43% pemberitaan, dan diberi nilai framing rendah—padahal ini menyangkut jantung dari demokrasi: keterbukaan dan akuntabilitas.
Media Sosial: Ruang Kritik yang Nyaring
Ketika publik diberi ruang tanpa kurasi, seperti di media sosial, potret yang muncul sangat berbeda. Isu pelayanan publik mendapat porsi tertinggi (36,8%) dan diberi label kritik sangat tinggi. Ini menunjukkan tingginya ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan dasar yang diterima.
Tak kalah penting, isu transparansi dan tata kelola mendapat nilai kritik sangat tinggi pula (31,6%). Ini menjadi indikasi bahwa publik tidak hanya kecewa terhadap pelayanan teknis, tetapi juga terhadap proses-proses pemerintahan yang tertutup, tidak partisipatif, dan sulit diakses.
Jurang yang Mengkhawatirkan
Ketidaksesuaian ini patut diperhatikan serius, bukan hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh media. Ketika media cenderung menyajikan narasi aman, dan menghindari kritik tajam, maka fungsi kontrol sosial media menjadi lemah. Di sisi lain, publik yang merasa tidak didengar memilih melampiaskan kekecewaannya di media sosial—yang meskipun nyaring, kerap dianggap informal dan tidak terstruktur.
Diskrepansi ini adalah gejala dari krisis legitimasi narasi. Kita sedang menyaksikan institusi-institusi informasi kehilangan kredibilitasnya karena tidak merefleksikan suara riil masyarakat.
Menutup Jurang, Memulihkan Kepercayaan
Media harus kembali pada posisi kritisnya, tidak sekadar menjadi kanal komunikasi satu arah dari kekuasaan. Pemerintah juga harus belajar mendengar, bukan hanya merespons ketika sorotan sudah terlalu tajam untuk diabaikan.
Diskusi dan partisipasi publik bukanlah ancaman. Justru dari situlah kualitas pemerintahan diuji dan ditingkatkan. Narasi yang baik bukan yang membuat nyaman, tapi yang jujur dan berpihak pada realitas.
Penulis adalah peneliti isu komunikasi publik dan tata kelola pemerintahan.
Tulisan ini merupakan bagian dari hasil riset konten terhadap representasi isu pemerintahan dalam media daring dan media sosial.